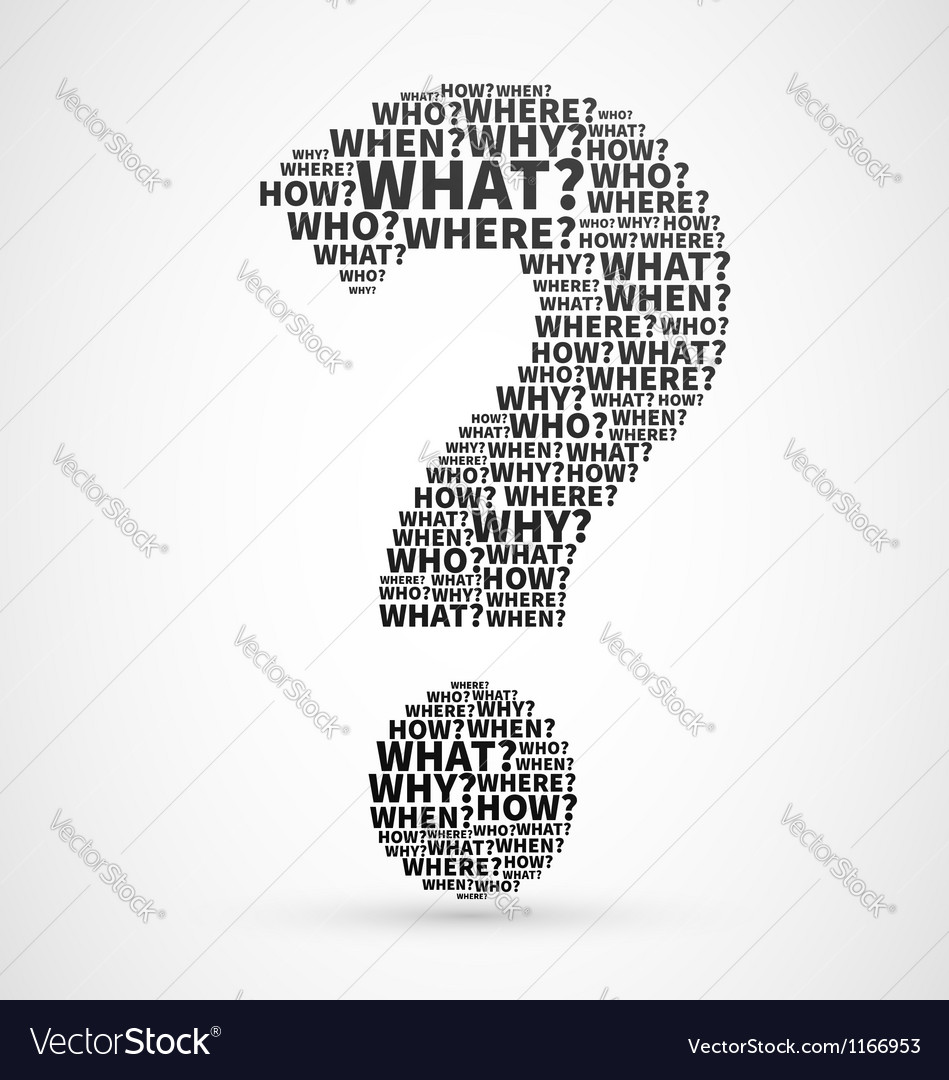As for me, all I know is that I know nothing.
True knowledge exists in knowing that you know nothing.Pernyataan Socrates itu adalah sebuah ironi ketika manusia seakan-akan telah mengetahui segala sesuatu dan menganggap apa yang diketahuinya adalah yang paling benar. Pengetahuan manusia mempunyai batas, tetapi apakah ketidaktahuan juga merupakan sebuah pengetahuan, masih merupakah hal yang gelap. Adalah sesuatu yang menyenangkan untuk menjadi tahu akan sesuatu dan terlebih lagi menyadari bahwa kita mengetahuinya. Tetapi jauh lebih menyenangkan untuk selalu dan tanpa henti mencari tahu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menandakan ketidaktahuan terhadap segala hal, dan bahkan terhadap apa yang telah diketahui. Itu menandakan kita masih hidup dan otak kita masih bekerja.
Pengetahuan pertama dimulai dengan sebentuk pertanyaan, sama seperti yang diajukan para filsuf terhadap hal apapun yang mengganggu keseimbangan penalaran dan perasaannya. Setelah pertanyaan itu terjawab muncul pertanyaan berikutnya, dan berikutnya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tak akan pernah terjawab sampai bumi ini kiamat atau sampai kita telah menemukan sebuah teori yang “maha tahu”. Banyak yang mengatakan kita akan berhenti mencari tahu ketika kita telah menemukan sebuah teori yang telah mengetahui segala hal.
Wait a minute !!! Dari mana kita tahu bahwa “teori” itu telah mengetahui segalanya, sedangkan yang membentuk “teori” itu adalah manusia, dan manusia belum mengetahui segala hal. Yang paling logis adalah ketika manusia membentuk “teori” itu, manusia telah mengetahui segalanya. Dan jika demikian untuk apa lagi “teori” seperti itu, kecuali untuk masuk tong sampah pengetahuan.
Mungkinkah manusia mengetahui segala hal ? Kita tidak berbicara tentang Tuhan, yang menurut kepercayaan manusia, mengetahui segala sesuatu alias Maha Tahu. Jikalau berbicara tentang Tuhan, kita tidak akan berbicara lagi masalah logika. Melogikakan Tuhan adalah seperti menarik sesuatu yang profan kedalam perdebatan pemikiran manusia yang terbatas. Kita membincangkan manusia.
Sepanjang sejarah manusia, usaha manusia selalu berawal dari mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Mencari tahu, memahami dan berusaha menjelaskan fenomena-fenomena alam di sekitar adalah seperti sebuah standar prosedur. Walaupun terkadang pemahaman dan penjelasannya bersifat spekulatif dan metafisis. Mungkin hal inilah yang membedakan antara sekedar mencari tahu dan memahami dengan mencari tahu, memahami, dan menjelaskannya. Semua itu membutuhkan peralatan yang bernama nalar, rasio, atau akal. Dan juga membutuhkan metode-metode tertentu seperti deduktif, silogisme, induktif, dan yang lainnya. Semua itu adalah usaha mencari tahu. Dari usaha itu terbentuklah semacam pengetahuan yang bisa saja digeneralisasikan dengan hal-hal yang mirip dan menyerupai fenomena yang telah diketahui.
Apakah itu berarti kita telah mengetahui semua hal dari fenomena tersebut? Tergantung. Tergantung ? Iya, tergantung dari mana kita melihatnya. Jika melihatnya dari sudut fenomena yang kita pahami dan jelaskan, memang kita telah mengetahuinya, bahkan sampai sekecil-kecilnya. Tapi kita pasti telah mengetahui fenomena gunung es, atau fenomena kesadaran-ketidaksadarannya Freud, atau bahkan dalam fisika yaitu prinsip ketidakpastian. Apa yang kita lihat (ketahui) adalah sebagian dari apa yang sebenarnya ada, dan apa yang telah kita ketahui pasti justru mempunyai sisi ketidakpastian atau dengan kata lain sisi ketidaktahuan. Bagaimana menerangkan ini ? Memang rumit. Tetapi secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketika kita ingin mengetahui sesuatu kita tidak pernah memperhitungkan semua hal yang mungkin berhubungan, walaupun sangat kecil, dengan apa yang ingin kita ketahui. Kita terbiasa mengontrolnya secara parsial atau menganggapnya ceteris paribus atau justru mengabaikannya.
Tetapi seperti kata Socrates diatas, kita masih menjadi manusia ketika kita tidak mengetahui dan kita sadar bahwa kita tidak mengetahuinya. Masih menjadi manusia ? Iya, masih menjadi manusia dan belum menjadi setan maha tahu. Setidaknya kita masih menggunakan otak dan peralatan-peralatan lainnya untuk mencari tahu. Logika ketidaktahuan tidak berasumsi bahwa yang tidak kita ketahui adalah sesuatu yang gelap dan tak akan pernah diketahui. Bukan itu. Yang tidak diketahui adalah sesuatu yang akan diketahui, tetapi tidak tahu kapan. Yang tidak diketahui pun bukan berarti bahwa bagian itu bukan milik manusia. Suatu saat akan menjadi milik manusia. Kapan ? Sekali lagi, tidak tahu.
Sekarang kita beranjak ke pengetahuan tentang Tuhan. Apakah kita tahu bahwa Tuhan itu ada ? Gunakan akal dan rasio dan jangan gunakan perasaan. Secara nalar, pengetahuan kita tentang Tuhan menempati sisi terlemah dari segala jenis pengetahuan yang kita punya. Tuhan itu ada, kata kita, tetapi pengetahuan itu bercampur dengan perasaan kita tentang adanya Tuhan dan juga keimanan kita tentang adanya Tuhan. Mungkin bagian ini akan terlihat terlalu empirik dan mengabaikan bentuk pengetahuan dan sumber pengetahuan lain.
Sejak runtuhnya abad pertengahan, yang terkadang membuat akal menyerah terhadap iman, orang mulai beralih ke pencerahan dengan menggunakan akal sebagai patokan untuk memahami sesuatu. Iman dan perasaan di kesampingkan. Orang lalu melihat fenomena secara empiris dan mengolahnya dengan akal dan nalar. Termasuk fenomena tentang Tuhan. Di jaman ini orang tidak akan menjadi seorang Giordano Bruno yang lain. Pemikiran kritis, itu mungkin tema utama sejak abad pencerahan rasio sampai jaman sekarang. Segala sesuatu dipikirkan secara kritis, dan jika tidak menyentuh akal dan nalar manusia, harus dibuang jauh-jauh dan diperlakukan seperti gereja memperlakukan para bidah abad pertengahan.
Lalu orang mulai merasa akal tidaklah cukup untuk menjadi penjaga gawang sebuah pengetahuan. Perasaan dan emosi mulai dilirik, dan tema baru mulai muncul dengan jargon utamanya : Perasaan adalah pengetahuan. Itulah yang membuat karya-karya seni besar dari para seniman besar lahir dan menjadi semacam pengetahuan baru. Setidaknya akal tidak lagi menentukan sebuah “kebenaran”, dan perasaan dan emosi bisa menjadi sumber pengetahuan itu sendiri.
Abad XX dimulai dengan pertumbuhan agama yang sangat pesat di dunia dan kesadaran orang terhadap agama mulai berubah. Dari menjauh menjadi mendekat. Kesadaran keagamaan menjadi sebuah tema baru perkembangan pengetahuan, bahwa sesuatu yang di yakini dan diimani juga adalah sebuah pengetahuan. Iman dan kepercayaan adalah pengetahuan. Dan itu berkembang hingga sekarang.
Sejarah diatas menjadikan contoh bahwa perasaan dan keimanan juga dapat menjadi sumber pengetahuan, dan bukan hanya akal dan nalar yang empirik. Mungkin agak lupa diterangkan di awal bahwa, selain dapat dijelaskan sebuah fenomena haruslah dapat dibuktikan. Sebuah pengetahuan adalah seperangkat bukti yang kuat dari penjelasan-penjelasannya. Jika kita beranjak dari sini, perasaan dan keimanan akan menjadi bagian yang lemah dari suatu pembuktian. Justru akan menjadi pembuktian subyektif yang tidak lagi berpusat pada fenomenanya tetapi berpusat pada manusianya.
Pernyataan Sartre terasa akan semakin menggelisahkan kalangan tertentu,”Ada rongga kosong berbentuk Tuhan dalam kesadaran manusia”. Apakah itu berarti Tuhan pernah hadir dan kemudian menghilang lenyap seiring perkembangan jaman ? Kalau itu diiyakan berarti Tuhan itu ada, walaupun kemudian menghilang. Atau pernyataan Nietzsche, “Tuhan telah mati, kita telah membunuhnya”. Itu juga berarti Tuhan itu ada, walaupun kemudian manusia telah “membunuhnya”. Sartre dan Nietzsche yang jelas-jelas merupakan filsuf eksistensialis masih mengakui keberadaan Tuhan, walaupun kemudian dinegasikannya. Nietzsche adalah seorang atheis, dan kemudian menjadi seorang antiteis, yang menentang keberadaan Tuhan. Sartre adalah seorang agnostik, yang menganggap ada atau tidak adanya Tuhan tidak berpengaruh apa-apa bagi manusia.
Tetapi benarkah Tuhan itu ada ? Jika kita menggunakan akal dan nalar empiris, kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak ada suatu penjelasan tentang Tuhan, dan tidak ada fakta dan bukti obyektif yang dapat diolah akal dan nalar manusia yang merujuk kepada keberadaan Tuhan. Jika kita menjadikan akal dan nalar sebagai petunjuk kita berdiri, maka Tuhan ada di luar kita, bahkan ada diluar bayangan kita. Dengan kata lain, apapun yang kita pakai untuk menjelaskan apa itu Tuhan dan siapa itu Tuhan sepanjang kita masih menggunakan akal dan nalar, Tuhan tetap tidak ada. Apa yang dapat dikatakan lagi.
Tetapi apakah berarti, menurut akal kita, jika Tuhan itu tidak ada masih merupakan sebuah “setengah pengetahuan”. Jika kita memakai fenomena gunung es di tengah laut, berarti apa yang kita ketahui tentang Tuhan, dan dengan pernyataan utamanya : Tuhan tidak ada, masih berupa apa yang kelihatan dan kita ketahui ? Bagaimana dengan yang tidak kelihatan dan tidak kita ketahui. Jika yang kita ketahui adalah “Tuhan tidak ada”, hal itu dapat membuka kemungkinan bahwa apa yang tidak kita ketahui adalah “Tuhan itu ada”. Semacam kontradiksi memang, tapi jawabannya adalah iya. Logika ketidaktahuan kita justru dapat membawa manusia kepada suatu misteri pemahaman bahwa Tuhan itu ada, dengan mennegasikan pernyataan utamanya. Apa yang tidak diketahui manusia dapat membuat penalaran utama sebagai inti akan menguap, dan membentuk penalaran ketidaktahuan yang baru.
Dengan kata lain Tuhan itu ada dalam ketidaktahuan manusia. Ketidaktahuan yang merupakan perlawanan terhadap arus utama pemikirannya yang menggunakan akal dan nalar. Pertanyaan sulit lain yang juga timbul adalah, apakah ketidaktahuan itu bentuk dari perasaan dan keimanan manusia ? Jawabannya : tidak tahu. Bagaimana seseorang mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Hal itu akan melanggar prinsip logika bahwa sesuatu tidak dapat menjadi X dan Y sekaligus pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengetahui dan tidak mengetahui sekaligus terhadap sesuatu pada saat yang bersamaan. Kita bisa berspekulasi bahwa mungkin apa yang tidak kita ketahui adalah perasaan kita, atau iman kita. Tetapi sekali lagi jika menggunakan akal dan nalar, saya mengatakan TIDAK TAHU.